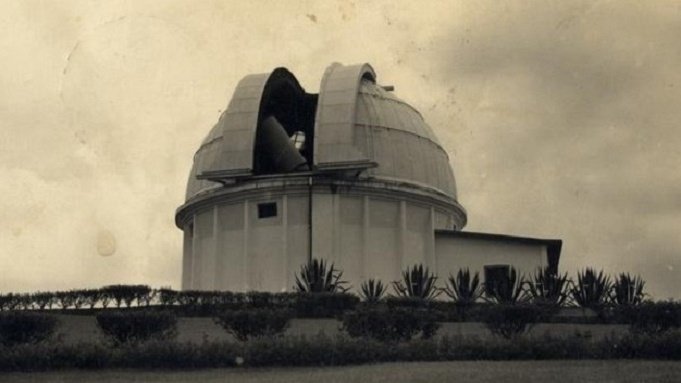Hari Masyarakat Adat Nasional diperingati pada tanggal 13 Maret setiap tahunnya. Hari Masyarakat Adat diperingati dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan keragaman adat, budaya dan suku bangsa di Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa makna dari “Bhineka Tunggal Ika” memanglah didesain untuk menyatukan berbagai suku, adat, budaya dan bahasa yang berada di berbagai belahan wilayah Indonesia.
Dikutip dari kata data, di Indonesia pada 2020, ada sekitar 70 juta Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air. Adapun sebaran Komunitas Adat terbanyak berada di Kalimantan dengan jumlah mencapai 772 Komunitas Adat dan Sulawesi sebanyak 664 Komunitas Adat. Adapun di Sumatera mencapai 392 Komunitas Adat, Bali dan Nusa Tenggara 253 Komunitas Adat, Maluku 176 Komunitas Adat, Papua 59 Komunitas Adat dan Jawa 55 Komunitas Adat.
Namun meskipun hari adat nasional telah diakui secara resmi oleh negara dan diakui dalam UUD 1945 (Undang-undang Dasar 1945), namun persoalan eksistensi dan konflik masyarakat Indonesia saat ini juga terus muncul, bahkan termarginalkan terutama dalam masalah konflik lahan atau agraria.
Masyarakat Adat: Antara Pengakuan, Konflik, dan Perjuangan Hak
Konsorsium Pembaruan Agraria dalam siaran persnya mencatat bahwa, Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria.

Masyarakat adat Suku Awyu misalnya, hutan mereka terancam untuk perkebunan sawit, sehingga mereka tergerak untuk menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL), seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro, bagian dari Suku Awyu. Dan ini hanya satu dari sekian kasus-kasus serupa yang banyak terjadi di suku-suku adat lain di Indonesia.
Padahal masyarakat adat adalah garda terdepan dalam menjaga alam dan hutan. Keberadaannya bukan hanya untuk menjaga kearifan lokal yang sudah diturunkan dari nenek moyang namun juga memastikan sumber daya alam bisa dinikmati oleh anak cucu dimasa depan. Ada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat adat untuk menjaga alam, mereka terikat dan terkait dengan alam, penjaga ekosistem sehingga bisa mencegah berbagai bencana yang muncul akibat masifnya kerusakan ekosistem yang masif saat ini terjadi.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menganggap bahwa marginalisasi yang terjadi pada masyarakat adat berawal dari adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, dalam analisisnya, mengungkapkan bahwa undang-undang ini menjadi pemicu disfungsi pemerintahan adat. Dualisme kepemimpinan antara kepala desa dan kepala adat menciptakan ketegangan internal, mengeksploitasi kelemahan struktural dan normatif dalam struktur pemerintahan.
Kepala desa, sebagai penguasa formal, bertindak di bawah otoritas legal formal, sedangkan kepala adat mengandalkan otoritas informal yang diberikan oleh Masyarakat Adat. Hasilnya, terjadi konflik kepemimpinan dan dualisme pemerintahan yang merugikan Masyarakat Adat secara sistematis. Marjinalisasi ini tidak hanya menciptakan keretakan kepemimpinan tetapi juga berdampak luas pada krisis kepemimpinan, urbanisasi paksa, disintegrasi komunitas, dan eksploitasi sumber daya alam. Penghancuran hutan secara tak terbatas di luar Jawa menjadi simbol eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan yang diterapkan oleh Masyarakat Adat secara turun-temurun.
Baca juga: Sulapa Eppa, Filosofi Masyarakat Bugis Memandang Alam Semesta
Dalam konteks perjuangan ini, RUU Masyarakat Adat menjadi landasan hukum yang krusial. RUU ini diharapkan dapat memberikan pengakuan formal dan perlindungan yang konkret terhadap hak-hak Masyarakat Adat, membuka jalan menuju pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan.
Penulis: Kori Saefatun
Editor: Nugrah
Sumber:
- https://news.detik.com/berita/d-6616391/serba-serbi-hari-masyarakat-adat-13-maret-dan-cara-memperingatinya
- https://katadata.co.id/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat
- https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/
- https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo